Lila pulang
larut lagi. Aku telah menunggunya berjam-jam dengan rasa cemas yang makin
membingungkan. Istriku tidak sanggup lagi melawan kantuknya. Sebelum masuk
kamar ia mcnyerahkan persoalan itu kepadaku. Barangkali ia juga sudah bosan
berulang-ulang memberikan nasihat tanpa mendapat tanggapan dari Lila.
Pukul dua
malam, akhirnya sebuah sedan berhenti di depan rumah. Lila turun diikuti oleh
dua orang teman lakinya. Aku segera menyalakan lampu depan dan membuka pintu.
Maksudkn supaya mereka jangan lagi ngobrol di
teras karena hari sudah jaiuh malam. Tapi begitu aku buka pintu,
sementara angin malani langsung menggosok mukaku, kulihat Lila sedang pamitan
dengan kedua kawannya.
Aku tahu betul
bahwa mereka melihatku. Tapi dengan hangat sekali; dan ini membuatku tiba-tiba
merasa risi dan rnalu, salah seorang kemudian memeluk dan mencium Lila. Sesudah
itu yang satu lagi. Aku memalingkan muka pura-pura tak melihat. Tapi mereka tak
segera masuk. Masih ada lagi beberapa perjanjian yang mereka buat. Kemudian
baru Lila masuk.
Lila
mengenalkan kedua kawannya kepadaku. Dengan dingin kujabat tangan mereka. Tapi aku masih menunggu beberapa lama lagi,
sebelum mereka kemudian pergi. Aku menarik napas panjang. Lila masuk, membuka
sepatu dan terus ke kamarnya. Aku masih sempat
memandang ke halaman. Beberapa lama tercenung. Memilih apa yang
sebaiknya dilakukan. Aku ingin mengharigai spontanitas. Aku tak suka dikatakan
kolot. Aku tak mau dikatakan menekan anak. Tapi aku tersinggung dan malu
sekali.
Perlahan-lahan
aku masuk. Mematikan lampu depan. Tetapi masih belum dapat memutuskan apa-apa,
sampai kudengar suara musik lamat-lamat dari kamar Lila. Aku rasa aku tak boleh mendiarnkan saja.
Setidak-tidaknya untuk mengurangi bebanku sendiri. Ini barangkali yang
kelimapuluh atau keseratus kalinya aku bimbang memilih sikap. Antara menganggap
Lila yang masih berusia 18 tahun - sebagai anak kecil atau sebagai anak remaja
yang bisa diajak berdiskusi.
Akhirnya aku masuk juga ke dalam kamar. Lila sedang
berbaring masih dalam pakaian yang tadi sambil mengisi teka-teki silang.
Meskipun acuh tak acuh, aku kira ia sudah tnenduga aku akan masuk dan
memberikan nasihat-nasihat lagi. Cuma mulutku tak segera ngomong. Aku hanya
duduk di sisi tempat tidurnya. Lila menoleh tenang.
“Ada
“Ya.”
Ia menggangguk.
“Kelihatannya Papa tidak senang.”
“Ya.”
“Karena Lila pulang larut lagi? Kan
Aku mengangguk.
“Memang.”
Dan tiba-tiba segalanya jadi lancar. Aku segera
menumpahkan perasaanku. Beban rasanya terlalu keras menghimpitku yang setiap
hari sudah cape kerja
“Papa malu Lila. Papa jadi sulit lagi sekarang. Apa
papa harus marah atau bagaimana. Papa tidak ingin kamu merasa papa tekan,
merasa dibatasi. Papa ingin megajak kamu ikut memikirkan persoalan-persoalan
yang ada di sekitar dirimu. Kau kan kan
Lila berhenti mengisi teka-teki.
“Lila jadi tidak mengerti. Itu kan
biasa, Pa.
“Berciuman dengan dua orang lelaki di depan papa,
papa kira itu bukan soal biasa. Caranya dia menciummu membuat papa menjadi
malu. Seakan-akan dia tidak menghiraukan kehadiran papa, padahal dia lihat.
Kalau papa tidak ada, itu adalah urusanmu. Tapi papa ada di situ, dan papa
tidak kenal siapa dia, barangkali itu juga hal biasa buat kamu. Tapi kan
“Lho Papa mengajar Lila tidak terus terang?”
“Bukan. Papa sendiri berterus-terang sekarang.
Inilah perasaan papa. Papa tidak marah, kamu jangan membela diri dulu. Coba
dengarkan apa perasaan papa. Kamu boleh terima, boleh tidak.
“Tapi kamu harus tahu apa yang saya rasakan waktu
kamu ciuman tadi. Lila tidak merasa papa tekan kan
“Tidak.”
“Nah. Yang papa rasakan adalah malu. Kalau itu cuma
teman biasa, mengapa harus berciuman begitu. Semua itu menyebabkan papa jadi
berpikir, bagaimana sebenarnya kamu membentuk persahabatan dengan
kawan-kawanmu yang lelaki. Mengapa mereka berani melakukan itu di depan saya,
ayah kamu, tanpa perasaan segan. Saya anggap mereka tidak sopan. Apalagi saya
tidak kenal mereka. Coba apa yang harus papa lakukan?”
Lila mengeluh.
“Kalau begini saya jadi tidak mengerti deh, mau
apa.”
“Lho papa tidak melarang, papa takut sekali kalau
kamu mengatakan bahwa papa sudah menekanmu. Tapi kamu harus dapat merasakan perasaan papa kan kan
“Udah deh, Pa, sekarang Papa katakan saja Lila
harus bagaimana.” Aku mulai marah.
“Lila, ini bukan hanya persoalan papa. Kamu yang harus menentukan apa yang harus kamu
lakukan. Papa cuma ingin mengutarakan perasaan papa dan papa ingin mendengar
sebenarnya kamu risi tidak melakukan
hal-hal tadi? Atau kamu menganggap itu pantas? Kalau pantas, ya barangkali papa
harus mulai dari sekarang
membiasakannya. Bisa kok. Semuanya bisa dibiasakan asal sudah diniatkan. Masak
tidak bisa? Kamu merasa risi atau tidak?”
“Saya kira itu biasa.”
Aku tertegun.
“Biasa? Lalu apa bedanya teman biasa dengan pacar.
Apa kamu menganggap mereka semua pacarmu? Atau bagaimana? Papa risi kok.”
Lila menyentuh tanganku.
“Pa,
saya sungguh tidak ingin menyusahkan Papa.”
“Tapi kamu sudah membuat saya merasa malu seperti
itu. Dan bukan sekali ini. Hanya baru sekarang
papa bicara. Apa toh sulitnya untuk
membatasi sedikit pergaulan. Bukan berarti tidak boleh bergaul. Bukan berarti tidak boleh bebas bergaul.
Bukan berarti tidak boleh ciuman.
Kalau kamu ulang tahun dan teman-temanmu mencium kamu di depan papa, papa anggap itu sopan. Tapi ini, mereka
memperlakukan kamu seperti barang mainan tanpa perasaan segan justru di depan
papa kamu sendiri. Ini kan
Tiba-tiba aku berhenti. Selama bicara, untuk
mendapatkan konsentrasi aku memandang
ke sudut lain. Sekarang aku lihat Lila
sudah tertidur memeluk guling. Mulutnya menganga sedikit. Mukanya masih penuh
rias. Pipi dan bibir merah. Kelopak mata biru. Ia mendengkur lunak. Tampaknya
sangat lelah. Barangkali ia sudah
ajojing habis-habisan. Di samping itu ia memang banyak kegiatan. Fisiknya memang membutuhkan istirahat.
Aku pandangi mukanya yang cantik. Muda dan
kelihatan tidak bersalah. Tak ada kata-kata lagi yang bisa menembus kantuk itu.
Ia tidur seakan-akan sedang mendengarkanku. Tapi jaraknya begitu jauh. Aku
merasa sedih dan tua. Sementara itu jengkel bukan main. Tanganku gemetar. Aku
ingin mengambil gelas dan membantingnya ke lantai. Barangkali itu bisa
menyalurkan tenaga yang mendadak bergumpal.
Aku berdiri dan mematikan radio. Sebenarnya aku
dapat menebarkan selimut yang masih terlipat rapi di kaki Lila. Tetapi tibatiba
aku merasa harga diriku bangkit. Setiap malam, hampir setiap malam aku masuk ke
kamarnya untuk menutup jendela yang terbuka. Atau menyalakan obat nyamuk. Atau
mematikan radio yang terus terpasang sementara Lila sudah tidur. Seringkali
juga aku memakaikan selimut agar is tidak masuk angin. Bahkan pernah aku
membuka sepatu yang tak sempat dicopotnya.
Aku berdiri sebentar dalam kamar itu. Tiba-tiba aku
marah pada diriku sendiri karena kelemahan-kelemahanku. Dan kelemahan itu
sudah dipergunakan oleh Lila. Aku sudah kehilangan wibawa. Kalau aku berdiri
lebih lama dalam kamar itu mungkin aku akan terhasut. Boleh jadi aku akan
membentak. Atau sebaliknya, meraih selimut sambil membarut-barut kepalanya.
Untuk pertama kalinya aku kuat untuk tidak memilih
salah satu. Perlahan-lahan aku meninggalkan kamar itu. Rasanya seperti
meninggalkan sebuah dunia yang sedang sibuk. Untuk kembali ke duniaku. Dunia
seorang lelaki berusia 40 tahun. Dunia seorang bapak. Dunia seorang manusia
lain yang juga punya pribadi dan ego.
Aku kembali ke ruang depan. Membaringkan tubuh di
sofa sambil memandang ke luar jendela. Kegelapan dalam ruangan agak menenangkan perasaanku. Tapi aku
tetap merasa ada pisau sedang berjalan di seluruh tubuhku menuju ke kepala.
Beberapa kali aku tidur-bangun, tidur-bangun.
Terakhir cahaya terang menusuk dari jendela. Aku terbangun dengan mata sepat.
Hari masih pukul enam. Belum ada yang bangun, kecuali pembantu yang menyiapkan
sarapan.
Aku berdiri dengan buku-buku tubuh ngilu. Yang
pertama kuingat adalah Lila. Aku masuk ke kamarnya. Kulihat dia masih tidur,
kini membelakangiku. Masih tetap kekanak-kanakan. Ingin diperhatikan,
dimanjakan. Dan tanpa rasa berdosa. Lampu dalam kamar masih terang. Selimut
masih terlipat rapih. Aku tak berusaha untuk membangunkan atau menyelimutinya.
Meskipun aku tahu pagi itu ia ada janji jam tujuh dengan lelaki yang mengantarkannya
semalam.
Diam-diam aku berkemas untuk ke kantor. Mandi
seperti sembunyi-sembunyi, takut akan membangunkan seisi rumah. Kalau mereka
bangun aku akan terpaksa ngomong. Padahal yang paling kubutuhkan saat itu
adalah diam. Aku sudah terlalu banyak bicara dan terpaksa bicara karena
persoalan — bermacam-macam persoalan. Egoku memerlukan ketenangan. Aku merasa
membutuhkan waktu untuk diriku sendiri.
Waktu sarapan—yang juga kulakukan secara
diam-diam—anak istriku masih tetap tidur. Aku memakai sendok-garpu dengan
hati-hati. Kemudian aku panggil Izah, pelayan keluarga kami. Aku berikan
padanya uang belanja yang harus disampaikannya kepada istriku. Aku berikan juga
ongkos tukang yang sudah memperbaiki dapur dan sudah dijanjikan sejak kemarin.
Juga untuk disampaikan ke istriku. Kemudian, dengan agak berat, aku serahkan
juga amplop berisi uang untuk Lila, untuk membayar uang sekolahnya.
“Tidak ada pesan apa-apa Den?” tanya Izah.
Aku menggeleng.
Aku buka pintu depan dengan hati-hati. Masih
terlalu pagi untuk berangkat. Tapi aku harus menenangkan perasaan. Memulihkan
rasa maluku. Celakanya, begitu hendak menutupkan pintu kembali, kulihat istriku
sudah berdiri di ruang depan. Agaknya sudah sejak lama memperhatikanku.
Hampir saja hendak kuterangkan dengan alasan
dicari-cari, kenapa aku harus berangkat terlalu pagi. Tapi dia hanya mengangguk.
Kulihat juga matanya agak bengkak. Barangkali dia sudah menangis. Dia
mendekatiku. Kemudian tanganku dipegangnya.
“Aku mengerti perasaanmu,” katanya lirih.
Aku bingung juga.
“Perasaan apa?”
Ia menggeleng sambil menepuk-nepuk tanganku.
Tangannya memberi isyarat supaya aku jangan bicara.
“Aku mengerti. Kau perlu sendirian. Aku lihat
kemarin. Aku ngintip dari jendela. Aku tahu.”
“Maksudmu Lila?”
“Ya.”
Aku menarik nafas panjang. Hampir saja aku berusaha
membelokkan percakapan. Istriku memberiku isyarat lagi sambil menekan tanganku
lebih keras.
“Aku melihat Lila melakukan itu. Tapi aku, terutama
melihatmu. Aku dapat merasakan perasaanmu!” Aku hendak menjawab, tapi ia
segera memotong.
“Sudah, pergi saja ke kantor dulu. Aku paham, sejak
kamu mandi dan sarapan tadi. Bahkan semalam aku sempat meletakkan bantal di
bawah kepalamu. Aku tahu dan mengerti, kamu perlu sendirian. Mungkin kamu akan
dapat jawaban, bagaimana sebaiknya menerima semua ini. Pergilah. Kalau bisa
ngobrol dengan teman-teman dekatmu. Nanti Siang tak usah pulang. Makanlah di
luar dengan sahabatmu, supaya perasaanmu pulih. Sudah itu coba nonton bioskop. Ada
Aku terpesona.
“Kau tahu semua itu?”
Ia mengangguk.
“Semua perasaan-perasaanku?!”
“Ya,” katanya lirih. “Aku kan
Ia tak dapat menyembunyikan perasaannya. Air
matanya menetes. Aku jadi terharu. Aku
ingin membawanya masuk, tapi ia segera
memberi isyarat.
“Aku tak
apa-apa. Aku terharu pada perasaanmu yang sekarang tertekan. Pergilah dulu.”
Kata-katanya
kedengaran sangat jujur. Lagipula masak aku tidak tahu kapan dia
bersungguh-sungguh, kapan tidak. Aku kan
suaminya.
“Pergilah.”
Aku mengangguk.
Sambil memegang tas, aku melangkah keluar rumah untuk mencari Bajaj. Tapi aku
masih ingat pada Lila. Masih melekat rasa
malu, panas dan kebingungan ketika berdiri di depan pintu semalam,
sementara dia berciuman dengan temantemannya. Perasaan itu seakan-akan mulai
hendak diusir oleh perasaan yang kuperoleh di depan istriku tadi. Masih ada seorang
yang benar-benar berusaha memperhatikan perasaanku yang sudah digenjot oleh
anakku sendiri.
Akhirnya, aku
berhenti di pinggir jalan menunggu Bajaj.
Dan itu pula
akhir dari segala jawabanku, sementara ini. Akhir dari segala pertanyaan yang
harus kujawab. Mengapa aku takut punya anak. Karena aku takut menghadapi Lila,
sebagaimana yang sudah dihadapi oleh teman-temanku yang sudah berkeluarga. Dan mengapa aku belum kawin-kawin juga?
Takut tidak akan menemukan seorang istri, yang dapat mengerti perasaan-perasaanku
manakala sedang tergencet.
Jakarta,
16 Mei 1980

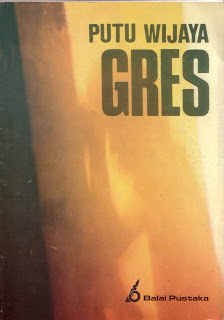
0 ulasan:
Catat Ulasan
Tinggalkan jejak sobat di sini